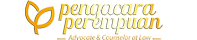Selama puluhan tahun, sistem hukum kita abai terhadap suara korban kekerasan seksual. Korban tidak hanya harus menanggung trauma fisik dan psikis, tetapi juga harus berhadapan dengan ketentuan hukum yang tidak “memihak” korban, yang lebih sibuk menghukum pelaku daripada memulihkan martabat korban yang dirampas.
Namun, angin perubahan kini berembus kencang dengan diundangkannya UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). KUHP lama warisan kolonial itu sering kali memposisikan kasus kekerasan seksual dalam delik kesusilaan, di mana fokusnya adalah pelanggaran norma susila di masyarakat, bukan pelanggaran atas hak asasi dan tubuh individu. Akibatnya, korban sering kali justru merasa “diadili kembali” di ruang sidang.
Hadirnya UU TPKS adalah sebuah perubahan besar. UU TPKS bukan sekadar aturan hukum, melainkan sebuah pernyataan politik bahwa negara tegak berdiri bersama korban. Hal ini sebagaimana tertuang jelas dalam Pasal 65 UU TPKS yang menyatakan bahwa “Korban berhak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Namun, perubahan ini baru benar-benar memiliki pijakan yang kokoh setelah KUHP Nasional disahkan. Mengapa demikian? Karena KUHP Nasional mengubah paradigma pemidanaan di Indonesia lewat Pasal 51 yang menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk “menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat,” sebuah semangat yang sangat kental dengan keadilan restoratif.
Dalam UU TPKS, pembayaran ganti rugi atau restitusi kepada korban adalah wajib, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 yang berbunyi, “Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan pemulihan.” KUHP Nasional memperkuat ini dengan menetapkan pedoman pemidanaan pada Pasal 54 ayat (1) huruf j, yang mewajibkan hakim mempertimbangkan “penderitaan korban” sebelum menjatuhkan putusan. Jika pelaku tidak mampu membayar, UU TPKS menyediakan jaring pengaman melalui mekanisme Dana Bantuan Korban (Victim Trust Fund). Meski mekanisme ini belum berjalan, setidaknya sudah ada jaminan nyata di atas kertas bahwa negara tidak membiarkan korban berjuang sendirian secara finansial.
Lebih jauh lagi, sinergi ini terlihat pada definisi pemerkosaan yang kini lebih luas dan tegas. Pasal 473 KUHP Nasional kini secara eksplisit mengatur hukuman bagi setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan persetubuhan. Penegasan ini memberikan perlindungan materiil yang kuat bagi korban yang selama ini sering terbentur pembuktian fisik yang sempit. Selain itu, bentuk-bentuk kekerasan modern seperti kekerasan seksual berbasis elektronik yang diatur dalam Pasal 14 UU TPKS kini mendapatkan payung besar dalam sistem pidana nasional kita yang lebih modern. Tidak ada lagi celah bagi pelaku untuk bersembunyi di balik kekosongan hukum hanya karena perkembangan teknologi.
Secara regulasi, Indonesia sebenarnya sudah menang telak. Kita memiliki salah satu perangkat hukum perlindungan korban terbaik. Namun, tantangan terbesarnya kini beralih pada implementasinya, budaya hukum para penegak kita. Polisi, jaksa, dan hakim harus menanggalkan kacamata lama yang sering kali masih terjebak pada pola pikir menyalahkan korban (victim blaming). Sinergi UU TPKS dan KUHP Nasional hanya akan menjadi macan kertas jika aparatnya tidak memiliki empati yang sama dengan semangat yang tertuang dalam pasal-pasalnya. Indonesia telah memasuki era baru di mana korban kekerasan seksual tidak lagi harus berbisik di kegelapan, melainkan bisa bicara dengan lantang karena dilindungi oleh benteng hukum yang kokoh. UU TPKS dan KUHP Nasional adalah janji negara bahwa keadilan tidak hanya berarti menjebloskan orang ke penjara, tetapi juga memastikan korban bisa kembali menjalani hidup dengan martabat yang utuh.